Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertanian, Prof. Bungaran Saragih pernah mengatakan, seandainya areal lahan seluas Jawa Barat ditanami sagu, maka seluruh rakyat Indonesia tidak akan kelaparan dan tidak perlu impor gandum. Luas Jawa Barat sebelum pembentukan provinsi Banten adalah 4.630.000 hektar. Dari luas areal tersebut, tiap tahunnya paling sedikit akan dapat dihasilkan 30.866.666 ton tepung sagu kering. Kebutuhan beras kita tiap tahunnya hanyalah sekitar 50.000.000 ton. Jadi kalau kawasan pasang surut di Sumatera, Kalimantan dan Papua ditanami sagu secara intensif dengan luas setara Jawa Barat sebelum pemisahan Banten, maka penduduk Indonesia jelas tidak akan kelaparan. Tetapi itu semua baru bisa terlaksana setelah jangka waktu 12 tahun. Sebab sampai dengan umur panen, dihitung sejak penanaman pertama, diperlukan waktu sekitar 12 tahun. Populasi tanaman per hektar kurang lebih 200 rumpun. Jumlah anakan dalam satu rumpun antara 3 sampai 4 individu dengan selisih umur 2 sampai 3 tahun. Kalau kita ambil jumlah minimal anakan 3 batang, dengan selisih umur maksimun 3 tahun, maka setiap 3 tahun sekali akan dapat dipanen 200 batang sagu. Dalam periode 12 tahun diperoleh tebangan 800 batang. Hasil tepung kering per batang sagu antara 100 sampai dengan 200 kg. Kalau kita ambil minimalnya, maka dari tiap hektar hutan sagu dalam 12 tahun akan dapat dipanen 80 ton sagu kering. Atau tiap tahunnya dapat dihasilkan 6,6 ton tepung sagu kering.
Angka tersebut adalah potensi minimal. Sebab dalam praktek, hasil per batang sagu bisa sampai 200 kg. Jumlah anakan dalam tiap rumpun dapat mencapai 4 batang dengan selisih umur hanya 2 tahun. Hingga potensi maksimal dari satu hektar hutan sagu per tahun, bisa mencapai 20 ton tepung kering. Dari luas areal seluruh Jawa Barat akan dapat dihasilkan 92.600.000 ton tepung kering (optimal) dan 30.866.666 ton (minimal). Atau angka rata-ratanya sebesar 61.733.000 ton. Ini semua sungguh sebuah potensi yang luar biasa. Sebab sagu justru bisa dibudidayakan di kawasan pasang surut yang ber pH (tingkat kemasaman tanah) 4,5. Dengan pH serendah itu, hampir tidak ada tanaman penghasil karbohidrat yang bisa tumbuh dengan baik. Keuntungan lain dari sagu adalah, tanaman ini hanya cukup ditanam sekali, dan setelah 12 tahun akan terus menerus dapat dipanen, tanpa perlu membuka lahan untuk penanaman baru. Sagu juga tidak perlu pupuk, pestisida dan lain-lain upaya budidaya seperti lazimnya pertanian modern. Hingga kita tidak perlu lagi didikte oleh IMF, World Bank dan lain-lain dalam meningkatkan produksi beras. Kalau hal ini bisa dilakukan, sebenarnya akan terjadi “revolusi” produksi karbohidrat secara murah dan massal. Sama halnya dengan “revolusi” produksi minyak nabati yang pernah terjadi pada kelapa sawit. Sebab tidak ada tanaman yang mampu menghasilkan karbohidrat semurah dan semassal sagu.
Namun karbohidrat sagu tidak mungkin menjadi substitusi, lebih-lebih menggantikan gandum. Meskipun nilai gizinya setara, sagu tidak mungkin diproses menjadi roti atau mi seperti seperti halnya gandum. Sebab dalam karbohidrat sagu tidak terkandung gliadine dan gliterin yang akan menimbulkan elastisitas dan bisa mengikat CO2 dalam proses fermentasi. Fermentasi terigu diperlukan bagi peningkatan volume, keempukan dan keremahan roti serta mi. Selama ini pemanfaatan sagu secara tradisional sebagai bahan pangan hanyalah dengan dibakar atau dibuat bubur. Namun sagu memiliki potensi yang sangat besar sebagai penghasil High Fructose Syrup (HFS) atau sirup berfructosa tinggi yang lazim juga disebut sebagai gula cair. Kebutuhan HFS sebagai substitusi gula pasir (sukrosa), di Indonesia mencapai 20.000 ton per tahun. Bahkan kalau ditambah kebutuhan untuk substitusi siklamat dan sakarin, kebutuhan per tahunnya akan mencapai 200.000 ton. Nilai HFS sendiri sekitar 10 sampai dengan 12 kali lipat dibanding nilai tepung sagu. Sebenarnya sejak tahun 1980an, pernah ada upaya untuk membangun industri HFS di Indonesia. Bahan bakunya singkong. Upaya ini telah menemui kegagalan, sebab suplai bahan bakunya tidak bisa kontinu. Panen singkong hanya terjadi setahun sekali selama sekitar 5 bulan pada musim kemarau.
Harga singkong sendiri, untuk kondisi saat ini juga sudah terlalu tinggi sebagai bahan baku HFS. Ekspor tapioka dan casava kita ke MEE selalu tidak pernah bisa memenuhi kuota. Selain karena suplainya terbatas, harga pati serta gaplek kita di dalam negeri, sudah lebih tinggi dari harga ekspor. Karenanya, untuk merancang kebutuhan HFS di masa mendatang, upaya penanaman sagu secara sistematis perlu mendapatkan perhatian serius. Industri HFS yang didukung oleh hutan sagu, memiliki keunggulan tersendiri karena murah dan adanya jaminan kontinuitas suplai bahan baku. Guna memproduksi 20.000 ton HFS, diperlukan bahan mentah berupa 45.000 ton tepung sagu kering. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dengan asumsi hasil minimal per hektar per tahun 6,6 ton tepung sagu kering, diperlukan areal hutan sagu monokultur seluas 6.818 hektar. Kalau HFS juga akan digunakan untuk mensubtitusi siklamat dan sakarin, maka areal hutan sagu yang diperlukan mencapai 68.180 hektar atau sepuluh kali lipatnya. Saat ini, di seluruh dunia hanya ada sekitar 2.000.000 hektar hutan sagu. Sekitar 1.000.000 hektar di antaranya ada di Indonesia. Upaya pengembangan sagu ini sangat dimungkinkan apabila menggunakan lahan-lahan pasang surut bekas tebangan HPH. Selama ini lahan bekas tebangan itu hanya dibiarkan terlantar karena tidak mungkin dimanfaatkan untuk tanaman budidaya.
Di Indonesia, dikenal ada dua spesies sagu. Pertama sagu sisika yang berduri (Metroxylon rumphii Mart.) dan kedua sagu beka yang tidak berduri (Metroxylon sago Rottb.) Sagu beka yang tidak berduri memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan sagu sisika yang berduri. Namun populasi sagu beka hanya 20% dari total populasi yang ada. Selama ini proses pengambilan pati dari batang sagu dilakukan secara tradisional. Mula-mula batang ditebang dan dibersihkan pelepahnya. Kemudian dipotong dan dibelah. Empulur sagu itu dicacah dan dihancurkan, diberi air lalu diremas-remas. Air yang melarutkan pati dialirkan ke tempat pengendapan. Setelah pati mengendap, air dibuang pelan-pelan. Di Papua, endapan pati sagu itu segera dibentuk menjadi lempengan besar dan langsung dibakar untuk mengawetkannya. Dengan cara demikian, rendemen tepung yang diperoleh kurang dari 10%. Dengan proses yang lebih baik, rendemen bisa ditingkatkan sampai 15%. Namun proses penepungan modern harus menggunakan mesin dalam pabrik yang menetap. Karenanya akan muncul kendala pembalakan (pengangkutan batang sagu). Sementara proses pengolahan tradisional justru untuk mengatasi kendala ini. Itulah sebabnya agroindustri sagu di masa depan harus memperhitungkan faktor transportasi dari lokasi penebangan ke tempat pengolahan.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 1.000.000 hektar hutan sagu yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Sementara itu kebutuhan sagu untuk memasok industri HSF guna substitusi sukrosa, siklamat dan sakarin hanyalah setara dengan 68.180 hektar. Jadi logikanya, pembukaan industri HFS dengan bahan tepung sagu sudah bisa dilaksanakan. Kendalanya, hutan sagu yang sekarang ini kita miliki memang benar-benar berupa hutan yang hanya bisa dieksplorasi oleh masyarakat setempat. Industri HFS harus dibangun dengan sebuah perencanaan jangka panjang yang matang. Setelah melalui tahap berbagai penelitian dan pengkajian, langkah berikutnya adalah pembukaan lahan, penanaman dan pembangunan sarana/prasarana. Terutama pembangunan jalan. Sebagai perbandingan, investasi pembukaan sebuah kebun kelapa sawit skala komersial dengan luas areal sekitar 50.000 hektar (3 pabrik), saat ini sekitar Rp 20.000.000,- per hektarnya. Dengan catatan, nilai lahan per m² masih di bawah Rp 100,- Dengan asumsi sama. total investasi yang diperlukan untuk sagu adalah 68.180 (hektar) X Rp 20.000.000,- = Rp 1.363.600.000.000,- (satu trilyun, tigaratus enampuluh tiga milyar, enamratus juta rupiah). Kalau dihitung suku bunga komersial 20% per tahun, maka selama tenggang waktu grace period 12 tahun, investasi tadi akan dikenakan suku bunga 12 X 20% = 240% atau nilainya akan menjadi Rp 4.636.240.000.000,- rupiah. Namun pola pencairan pinjamannya, harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan tiap tahunnya, hingga secara riil, apabila dihitung flat hanyalah sekitar 13% per tahun atau 156% selama 12 tahun. Berarti nilai pinjaman berikut bunganya hanya akan menjadi Rp 2.127.216.000.000,- (dua trilyun, seratus duapuluh tujuh milyar duaratus enambelas juta rupiah).
Produksi tahun I setelah jangka waktu 12 tahun, akan menghasilkan HFS sebanyak 200.000 ton. Asumsi harga tepung sagu kering (kadar air 14%), sekitar Rp 2.000,- per kg. Nilai HFS, sekitar 10 kali lipat nilai tepung sagu, berarti per kg. HFS harganya Rp 20.000,- Pendapatan kotor pada tahun I produksi ini akan mencapai 200.000 (ton) atau 200.000.000 (kg.) X Rp 20.000,- = Rp 4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah). Dengan pendapatan kotor setinggi itu, pada tahun I tersebut, sebenarnya seluruh biaya rutin sudah akan tertutup dan masih akan ada sisa untuk angsuran pinjaman dan biaya bunga. Ini semua tentu masih merupakan suatu perkiraan yang sifatnya sangat kasar. Dalam aplikasi di lapangan, akan banyak sekali dijumpai kendala yang pada akhirnya juga akan bermuara menjadi biaya. Terutama kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor-faktor off farm, di luar sektor agroindustri sendiri. Kebutuhan HFS sebagai substitusi sukrosa, sakarin dan siklamat, pada masa mendatang akan terus meningkat. Sebab industri makanan dan minuman memang cenderung akan memilih HSF dibanding sukrosa, siklamat maupun sakarin.
Nilai investasi sebesar 1,3 trilyun rupiah, dengan grace period 12 tahun, dengan luas lahan 68.180 hektar dan pendapatan kotor pada tahun I sebesar 4 trilyun rupiah, sebenarnya layak untuk didanai pinjaman komersial. Indonesia memiliki potensi alam bagi pengembangan sagu yang tidak dimiliki oleh benyak negara di dunia. Apabila upaya ini dilakukan, sebenarnya kita dapat sangat berkontribusi bagi pemenuhan pangan dunia. Sebab meskipun karbohidrat dari sagu tidak mungkin dapat menggantikan gandum, namun fungsinya sebagai bahan pangan berupa tepung, tetap harus diperhitungkan. Lebih-lebih kalau arah pengembangan sagu ini ditujukan bagi industri HFS. Fructose (fruktosa) adalah senyawa karbohidrat yang tergolong sebagai monosakarida dan heksosa. Sebab fruktosa hanya memiliki 6 atom C dan 6 atom O dalam molekulnya (C6H12O6). Sementara Sukrosa (sakarosa) dalam gula pasir adalah C12H22O11. Dalam kehidupan sehari-hari, fruktosa terdapat pada madu dan buah-buahan yang rasanya manis. Sementara sukrosa terdapat dalam gula tebu, gula kelapa, aren, lontar, nipah, bit, maple dan sorgum manis.
Most Popular
Created By SoraTemplates | Distributed by Blogging
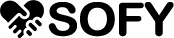
0 Comments